Perpustakaan dan Toko Buku Rasia Bandoeng
Oleh: Dongeng Bandung
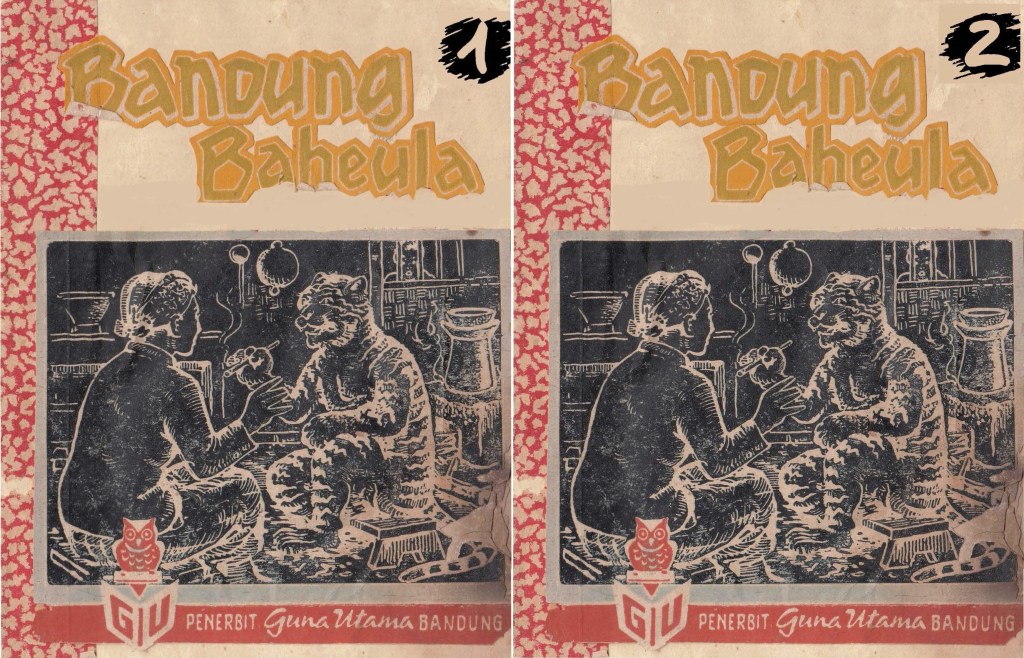
Buku Bandung Baheula yang terdiri dari dua jilid ini dikarang oleh R. Moech. A. Affandie dan diterbitkan serta dicetak oleh (penerbit dan) Pertjetakan Guna Utama, Bandung. Pada bagian “Pihatur ti Pajun” yang ditulis oleh Moech. Affandie sendiri tertera keterangan “Bandung, Djanuari 1969.”
Buku Bandung Baheula semestinya terdiri dari tiga jilid, karena pada halaman akhir Jilid-2 terdapat keterangan mengenai buku jilid ketiga ini dengan penjelasan bahwa buku tersebut lebih tebal, lebih lengkap, dan disertai pula oleh gambar-gambar. Bahkan sudah ada pula daftar isinya yang terdiri dari 10 cerita.
Namun sampai sekarang, buku Jilid-3 ini belum pernah terlihat fisiknya, sebagian kolektor menyebutkan bahwa buku Jilid-3 tidak jadi atau tidak pernah terbit dan tidak ada yang menerangkan alasannya. Yang jelas, tidak ada yang pernah melihat wujud buku Jilid-3 tersebut.
Mengenai isi buku pada bagian pengantar yang dijuduli Pihatur ti Pajun tadi diterangkan bahwa bahan-bahan yang diceritakan Affandie dalam buku ini kenging maluruh ti sepuh-sepuh anu kantos ngalaman, tapi setelah membaca isinya, ternyata sedikit banyak Moech. Affandie juga menggunakan buku-buku lama untuk mendukung cerita-ceritanya. Misalnya, ada De Toverlantaarn karangan K. Gritter atau Bandung en Haar Hoogvlakte yang memberi informasi soal nama ibukota Kabupaten Bandung lama, yaitu Krapjak, di Dayeuhkolot sekarang. Tapi ditegaskan juga bahwa tujuan penulisan buku ini hanya untuk hiburan semata.
Buku-buku yang disebutkan dalam cerita tidak selalu diberi keterangan secara lengkap, kadang hanya menyebut nama penulisnya saja. Misal saat Moech. Affandie menerangkan bahwa pada tahun 1897 batas-batas kota Bandung adalah Katja-katja Kulon di barat, Katja-katja Wetan di sebelah timur, Tegallega di sebelah selatan, dan Pabrik Kina di sebelah utara. Penduduknya, sekitar 40 ribu jiwa.
Dia menyebut catatan harian Juliaan de Silva tahun 1641, tapi tidak menjelaskan judul bukunya, dan ketika menerangkan keadaan Bandung tahun 1742, juga sama sekali tidak menyebutkan sumbernya. Jadi ya perlu agak hati-hati juga menyimak kisah yang disampaikannya, agar dapat membedakan mana yang kira-kira memang berdasarkan referensi tertentu dan mana yang merupakan rekayasa untuk cerita. Pada bagian pengantarnya Affandie juga sudah mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang sengaja dia ubah ketika menceritakannya kembali melalui buku ini.
Salah satu keunikan buku Bandung Baheula ini adalah Daftar Isi-nya yang terletak di halaman akhir, dan bukan di depan sebagaimana yang umum kita dapati sekarang. Entah, apakah cara seperti ini pernah jadi kebiasaan di masa lalu, atau karena ada alasan lain. Samar-samar teringat juga memang ada beberapa buku lain yang menempatkan daftar isinya di halaman belakang. Kedua jilid Bandung Baheula diberi ilustrasi yang dibuat oleh Rusli SW dan Urip. Sebagai informasi tambahan, kedua jilid ini sudah pernah juga disalin oleh Komunitas Aleut sekitar tahun 2015 untuk keperluan kegiatan belajar internal.
Pendongeng hari ini, Alex Ari, tidak membuat alur tertentu untuk menceritakan pengalamannya membaca dua jilid buku langka ini, lebih spontan dan mengalir berdasarkan apa yang diingatnya saja ketika bercerita. Seperti biasa, ada sejumlah buku bacaan tentang Bandung yang dibawanya, kali ini semuanya dalam bahasa Sunda. Karena keterbatasan ruang dan ingatan, di sini hanya akan kami ceritakan sedikit bagian saja yang disampaikan oleh pendongeng, terutama bagian “Istilah djeung Tetelehan”.
Bab yang terdapat pada buku Jilid-1 ini memang menarik karena banyak mention istilah-istilah atau nama-nama yang dahulu pernah populer dan menjadi keseharian warga Bandung, namun kini sudah mulai kurang dikenal lagi. Misalnya istilah cacing cau untuk para pemain selingan atau pengisi waktu jeda – biasanya anak-anak atau yang belum mahir – dalam pertandingan badminton, atau dulu istilahnya badingdong. Lalu istilah tot bray yang awalnya ditujukan pada kegiatan dansa-dansi sambil berpelukan, tapi kemudian ditambah menjadi van reup tot bray yang maksudnya berkegiatan semalaman suntuk seperti menonton wayang golek. Lebih kurang, dari gelap sampai terang, alias dari malam sampai pagi. Istilah ini juga digunakan oleh Kuncen Bandung, Haryoto Kunto dalam bukunya.
Pernah ada ungkapan populer sararedil Asnawi dibedil sararenang Lurah Cilengkrang beunang yang lahir dari suatu peristiwa pembunuhan di Kampung Talun, Majalaya, pada tahun 1920-an. Salah seorang warga kampung tersebut yang bernama Asnawi terkenal kaya raya. Suatu malam Asnawi mendapat kunjungan dari Lurah Cilengkrang yang bermaksud meminjam uang sebanyak 3000 rupiah, tapi ternyata Asnawi tidak bersedia meminjamkan. Kesal dan marah karena ditolak niatnya, Lurah Cilengkrang ngabedil (menembak dengan pistol) Asnawi hingga tewas seketika. Ungkapan sejenis itu yang pernah populer adalah ulah cekcok, bisi aya encek dibacok yang timbul dari peristiwa pembacokan seorang wartawan Sin Po yang tinggal di Jalan Karanganyar akibat persoalan pribadi.
Ada juga istilah diyasinkeun yang maksudnya mendapatkan perlakuan kasar dalam pertandingan bola. Istilah ini bermula dari seorang pemain Persib yang berasal dari Sumatera yang dikenal sering berani bermain kasar dan karena itu korban-korban yang kena dupak, kasepak, katengkas, kagaet, dst, sering diistilahkan sebagai diyasinkeun. Ada lagi istilah maen sabun yang lahir dari dunia olahraga worstelen atau gulat. Salah satunya adalah gulat antara Nafsirin yang pada zaman itu dikenal tanpa lawan, dalam sebuah pertandingan melawan Basrul yang datang dari Jakarta, sengaja mengalah untuk menghargai lawannya itu yang sama-sama berasal dari Kota Medan.
Istilah maen sabun kemudian digunakan meluas dalam bidang olahraga lain, bahkan juga digunakan dalam dunia jurnalistik seperti pernah terjadi dala polemik antara redaktur koran Sipatahunan dan redaktur koran Sinar Pasundan. Saling debat dan saling bantah berlangsung sengit antara dua redaktur itu, bahkan sampai seperti dua orang yang saling bermusuhan. Namun pada saat yang sama banyak warga kota yang memergoki keduanya berjalan bersama, terlihat bergembira dan sangat akrab. Akhirnya orang-orang pun menganggap polemik dalam kedua koran itu sebagai maen sabun saja.
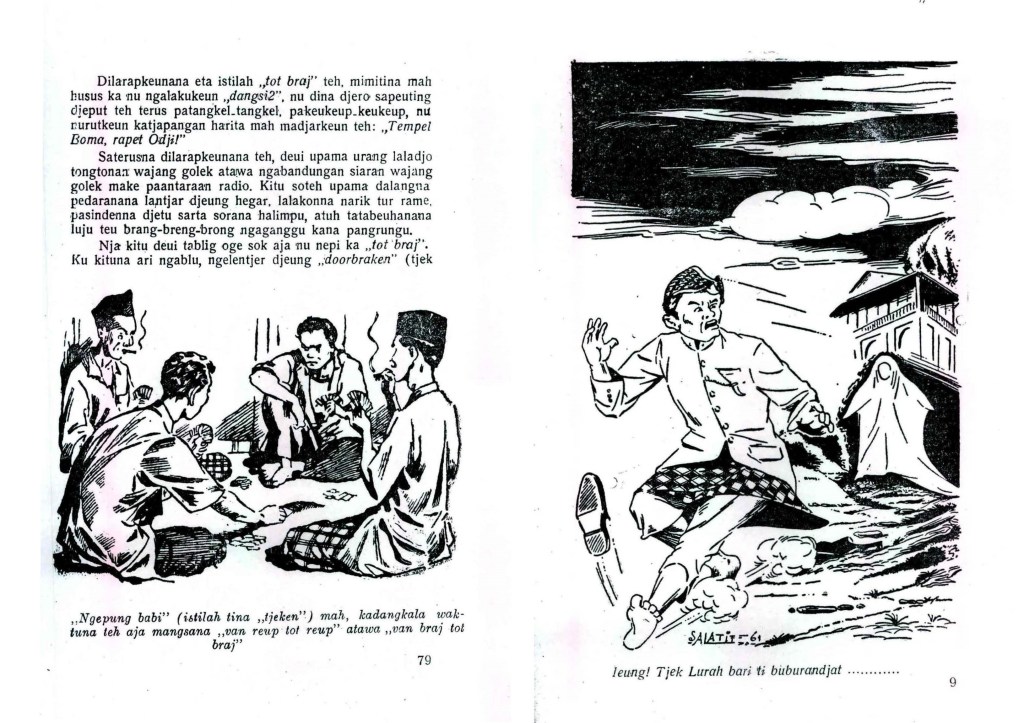
Selain istilah dan ungkapan seperti di atas, ada juga istilah yang berkaitan dengan orang atau tokoh tertentu. Misalnya, ada beberapa tokoh tempo dulu yang namanya sama dan untuk membedakannya masing-masing diberi julukan berdasarkan konteks tertentu, misalnya “Asep Berlian”, seorang pengusaha kaya dan tuan tanah terkenal keturunan Palembang yang bernama asli Kiagus Asep Abdullah bin Kiagus Haji Abdul Sjukur. Lalu ada nama “Sanusi Meja-bola” yang untuk sebagian pembaca akan langsung mengingatkan pada tokoh Sarekat Islam, Haji Sanusi, yang tinggal di Kebonjati. Rumah Haji Sanusi Meja-bola inilah yang ditumpangi indekos oleh Soekarno ketika kuliah di Bandung. Ketika itu Haji Sanusi masih berstatus suami-isteri dengan Inggit Garnasih. Cerita selanjutnya tentu sudah jadi pengetahuan umum para peminat sejarah Bandung.
Selain Sanusi Meja-bola, ada juga Sanusi Jago, dan orang-orang dahulu pasti sudah tahu siapa yang dimaksudkan, yaitu Sanusi yang tinggal di Gang Sim Cong yang pernah menjadi mertua dalang terkenal Umar Partasuwanda. Dialah ayahanda pesinden Arnesah yang pernah dibicarakan dalam tulisan ini. Masih ada lagi Sanusi lainnya, yaitu Sanusi Gendjlong yang sudah pasti maksudnya adalah Moh. Sanusi pengarang buku Gendjlong Garut dan Siti Rajati yang sempat dibuang ke Boven Digul karena terlibat dalam pemberontakan tahun 1926.
Julukan-julukan ini muncul dari sesuatu yang khas dari pengalaman hidup mereka, bisa tempat tinggal, keahlian atau prestasi, atau bisa juga dari tempat di mana mereka dimakamkan setelah wafat, seperti beberapa nama julukan bupati ini: Dalem Tjikundul, Dalem Dajeuhkolot, Dalem Karanganjar, Dalem Talun, Dalem Gentong, dan Dalem Gunung. Bupati lainnya berjuluk Dalem Dicondre karena sang bupati wafat wafat setelah seseorang menikamnya dengan condre (sejenis belati kecil). Di Cipatik, dari masa Kabupaten Batulayang, konon sang bupati pernah mengunjungi Sultan Sriwijaya di Palembang dan saat pulang diberi oleh-oleh gajah sehingga ia dijuluki Dalem Gajah, malah tempat pemandian gajahnya di sebuah lubuk Citarum pun dikenal dengan nama Leuwigajah.
Ada Bupati Sukapura yang berjuluk Dalem Sawidak karena memiliki anak berjumlah sawidak atau salah satu Bupati Galuh yang berjuluk Dalem Perbu karena karakternya yang merebu, yang di sini dijelaskan artinya sebagai lungguh ampuh kasinungan budi luhung perbawa luhur elmu-panemuna dina soal kabatinan, djembar kauningana dina bagbagan kaagamaan. Julukan Dalem Bintang disematkan untuk tiga orang bupati berbeda, masing-masing dari Bandung, Sukapura, dan Ciamis. Ketiganya mendapatkan julukan karena sebab yang sama, mendapatkan penghargaan bintang dari pemerintah Hindia Belanda karena jasa-jasanya.
Dalem Haji di Bandung adalah julukan untuk RAA Wiranatakusumah yang sudah melaksanakan ibadah ke tanah suci. Ada lagi Dalem Lutung, Bupati Ciamis, yang mendapatkan julukan tersebut karena sering mementaskan lakon sandiwara Lutung Kasarung, dan Dalem Gelung dari Sukabumi yang mendapatkan julukannya karena tata rambutnya masih disanggul walaupun tidak lepas dari bendo kasundaan.
Ada dua patih dengan julukan terkenal Patih Selong dan Patih Ternate. Patih Selong adalah julukan untuk R. Anggadikusumah yang dibuang ke Pulau Selong karena dituduh berkomplot dengan Raksa Praja membuat huru-hara di Priangan. Pada masa Hindia Belanda sudah menjadi kebiasaan di kalangan birokrat pribumi bahwa jabatan dan kekuasaan diwariskan kepada keturunannya. Hampir selalu dapat dipastikan anak seorang bupati atau wedana, kelak akan menjadi bupati dan wedana pula. Begitu pula yang ada dalam pikiran Raden Aria Anggadikusumah ketika ia menjabat sebagai Patih Polisi di pertengahan tahun 1800-an lalu.
Ayah Anggadikusumah pernah diangkat menjadi kepala cutak yang membawahi empat cutak, yaitu Cutak Cisondari, Cutak Rongga, Cutak Cihea, dan Cutak Kopo. Karena itu pada tahun 1822 ia mengajukan menyurati Residen Priangan dan memohon agar wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan ayahnya itu dikembalikan ke padanya. Namun Residen hanya memberikan dua cutak saja, yaitu Cutak Cisondari dan Cutak Rongga. Belum lagi harapannya terkabulkan, tiba-tiba tanpa alasan jelas, pemerintah Hindia Belanda memecatnya dari jabatan Patih Polisi.
Sementara itu pada tahun 1828 di wilayah Kabupaten Sukapura, seorang penduduk Cutak Karang bernama Raksa Pradja mengangkat diri sebagai raja dengan gelar Sultan Raja Kanoman. Tidak terlalu jelas apa latar belakang Raksa Praja berbuat seperti itu, namun tindakannya mengakibatkan ia ditangkap dan dibuang ke luar Jawa selama enam tahun dengan tuduhan melakukan penipuan dan pemakaian gelar kebangsawanan secara tidak sah. Sekembali dari pembuangan, tahun 1842, Raksa Pradja mendengar bahwa kawan lamanya, R.A. Anggadikusumah telah dipecat dari jabatan Patih Polisi. Saat itu Bupati Bandung, Wiranatakusumah sedang tidak ada di tempat dan situasi ini membangkitkan keinginan pada Raksa Pradja untuk mengambil alih kekuasaan Bupati Bandung dengan cara menyerang pusat kota Bandung. Inti cerita, Raksa Pradja memanfaatkan situasi ini untuk mengejar ambisinya mendapatkan kekuasaan tertinggi di Kabupaten Bandung.
Mengenai Patih Ternate, sudah cukup banyak ditulis orang karena dialah Patih Bandung Demang Somanagara – dikenal sebagai ayahnya Dewi Sartika – yang dibuang ke Ternate setelah dituduh mendinamit papanggungan di Tegallega saat pacuan kuda. ***